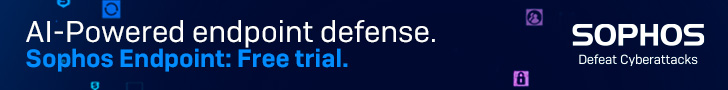Beritakota.id, Jakarta – Pemerintahan baru Indonesia baru berusia sepuluh bulan. Waktu yang masih singkat dalam ukuran sejarah, tetapi cukup menentukan arah perjalanan bangsa. Periode ini mestinya menjadi masa konsolidasi, pembangunan kepercayaan publik, dan fondasi awal menuju Visi Indonesia Emas 2045. Namun, tanda-tanda bahaya sudah muncul: ancaman non-state actor global di luar sana, dan luka demokrasi yang kian terasa di dalam negeri.
Wajah Non-State Actor
Kita tidak boleh naif. Non-state actor bukan sekadar istilah akademik atau bayangan abstrak. Mereka memiliki nama, agenda, dan rekam jejak. George Soros dengan jaringan Open Society-nya yang kerap dituding menumbangkan rezim melalui gerakan sipil; George Tenet, mantan Direktur CIA yang piawai mengorkestrasi operasi intelijen; Henry Kissinger yang selama puluhan tahun mengajarkan strategi “pecah belah dan kuasai”; hingga Paul Wolfowitz, arsitek perang Irak, yang ironisnya pernah menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.
Jejak mereka nyata: Irak hancur setelah invasi 2003, Suriah luluh lantak sejak 2011, Libya kehilangan kedaulatan, Ukraina terjebak dalam perang panjang. Polanya serupa: isu kebebasan dijadikan bendera, konflik internal dipelihara, lalu intervensi asing masuk dan menghancurkan kedaulatan negara.
Celakanya, mereka tidak bekerja sendirian. Ada kaki tangan di dalam negeri—tokoh, organisasi, bahkan lembaga—yang tanpa sadar dipakai. Banyak yang percaya sedang memperjuangkan demokrasi, padahal hanya menjadi bidak dalam permainan besar. Inilah bahaya laten yang harus kita waspadai.
Tragedi Umar: Luka Demokrasi yang Menyayat
Dalam situasi itu, kita dikejutkan dengan tragedi Moh. Umar Amarudin (30), seorang pengemudi ojek online asal Cikidang, Jawa Barat. Malam 28 Agustus 2025, di Jalan Penjernihan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Umar ditabrak mobil rantis Brimob yang sedang mengejar massa aksi. Tubuhnya terseret roda depan kanan kendaraan, dan nyawanya tidak tertolong di RS Pelni.
Video kejadian tersebar luas di media sosial. Warga berteriak menyelamatkan Umar, sementara mobil Brimob justru meninggalkan lokasi sebelum akhirnya dihadang massa. Hingga kini, polisi belum memberi keterangan resmi.
Ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah tragedi demokrasi. Dalam sebuah negara yang mengaku demokratis, hilangnya satu nyawa sipil akibat tindakan represif aparat adalah dosa besar. Demokrasi sejati menuntut penghormatan pada hak rakyat, bukan pengorbanan rakyat.
Kita sudah terlalu sering mengalami luka yang sama. 1998, empat mahasiswa Trisakti gugur ditembak aparat. 2019, aksi 21-22 Mei menewaskan sembilan orang. 2020, penanganan demo Omnibus Law melukai puluhan warga. Setiap kali itu terjadi, kepercayaan publik runtuh, luka kebangsaan semakin dalam. Apakah kita hendak mengulang babak kelam itu lagi?
Bahaya Represi: Hadiah untuk Non-State Actor
Setiap tindakan represif aparat, setiap nyawa rakyat yang melayang, adalah hadiah terbesar bagi non-state actor global. Mereka tidak perlu bersusah payah menyalakan api. Api itu kita ciptakan sendiri. Mereka hanya menunggu celah, lalu masuk, membesarkan perpecahan, melemahkan institusi, dan mengoyak persatuan bangsa.
Inilah ironi terbesar. Negara yang mestinya melindungi rakyat justru memberi bahan bakar bagi mereka yang ingin melihat Indonesia hancur. Represi bukan hanya kesalahan moral, tetapi juga kesalahan strategis.
10 Bulan: Momentum atau Bahaya?
Pemerintahan yang baru berusia sepuluh bulan ini harus memahami bahwa stabilitas politik dan kepercayaan rakyat adalah modal utama. Tanpa itu, agenda besar sebesar apa pun akan runtuh. Setiap langkah salah aparat bukan sekadar insiden, melainkan ancaman terhadap legitimasi negara. Sepuluh bulan adalah momentum untuk menguatkan fondasi demokrasi, bukan membiarkan luka baru bermunculan. Jika pemerintah gagal membaca tanda-tanda ini, Indonesia bisa terperosok ke jurang yang sama seperti Irak atau Suriah: negara yang hancur karena kelengahan internal yang dieksploitasi aktor asing.
Pengingat dan Seruan Persatuan
Kita Coop GERNAS, yang berisikan berbagai relawan pendukung Prabowo-Gibran, berdiri di garda depan untuk mengawal pemerintahan, menjaga rakyat, dan memastikan bangsa ini tidak jatuh ke dalam skenario asing. Kita boleh berbeda pandangan politik, tetapi kita tidak boleh membiarkan perbedaan itu dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa. Indonesia baru sepuluh bulan menapaki babak baru. Jangan biarkan luka demokrasi menjadi pintu masuk bagi tangan-tangan asing. Non-state actor menunggu kita lengah, menunggu kita terpecah. Jika kita tidak bersatu, Umar bukanlah korban terakhir. Persatuan adalah harga mati. Kita harus menjaga Indonesia, atau kita akan bernasib seperti Irak dan Suriah.