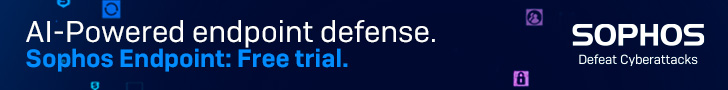Beritakota.id, Jakarta – Ada jenis horor yang tidak hanya ingin menakut-nakuti, tetapi mengajak penontonnya menatap sesuatu yang lebih gelap — bukan di luar sana, melainkan di dalam diri sendiri. Rosario (2025), film debut panjang Felipe Vargas, termasuk dalam jenis ini. Ia bergerak di persimpangan antara kisah keluarga, spiritualitas Latin, dan trauma yang diwariskan. Film ini bukan hanya tentang kutukan, tetapi tentang apa yang terjadi ketika manusia modern memutus tali dengan mitos dan asal-usulnya sendiri.
Latar dan Premis
Rosario “Rose” Fuentes (Emeraude Toubia) adalah pialang saham sukses di Wall Street. Ia hidup di jantung rasionalitas dunia modern — cepat, efisien, logis, dan berjarak dari segala yang spiritual. Namun kehidupannya berbelok ketika menerima kabar bahwa neneknya, Griselda, meninggal di apartemen tua di New York. Rosario datang untuk mengurus peninggalan keluarga, tetapi badai salju membuatnya terjebak semalaman di dalam apartemen itu.
Dari sinilah film memulai transformasi ruang domestik menjadi ruang psikis: setiap sudut apartemen, setiap benda, setiap bisikan menjadi pintu menuju masa lalu yang tak pernah selesai. Rosario menemukan artefak-artefak ritual aneh — tengkorak manusia, simbol-simbol Palo Mayombe, dan catatan yang menyinggung tentang “perjanjian darah.” Ia mulai menyadari bahwa keluarganya terikat oleh warisan spiritual yang tidak pernah ia pahami, dan bahwa keengganannya terhadap tradisi itu mungkin justru memperkuat kutukan tersebut.
Baca juga : Review Film The Toxic Avenger – Satir Kapitalisme Dan Luka Kemanusiaan
Atmosfer dan Sinematografi
Felipe Vargas menata Rosario sebagai film dengan ritme lambat dan ruang yang menekan. Kamera kerap berdiam lama di koridor gelap, membiarkan kesunyian menjadi bagian dari narasi. Apartemen Griselda tampil seperti tubuh yang hidup — penuh retakan, suara napas, dan gerak samar di balik pintu.
Sinematografernya, Nicolás Wong Díaz, menggunakan pencahayaan kontras yang menekankan perbedaan antara ruang modern (terang, putih, steril) dan ruang leluhur (redup, berdebu, penuh simbol religius).
Di titik-titik tertentu, film mengingatkan pada The Others (2001) karya Alejandro Amenábar atau His House (2020) — dua film yang sama-sama menempatkan horor sebagai metafora kehilangan tempat dan identitas. Namun Rosario menambahkan lapisan Latin yang khas: dunia spiritual Afro-Karibia, aroma dupa, bahasa doa, dan kehadiran yang tidak pernah bisa dipisahkan dari tubuh dan tanah.
Simbolisme dan Tema
Kekuatan utama film ini terletak pada kemampuannya menjahit antara horor psikologis dan krisis identitas kultural. Rosario bukan hanya melawan roh, tetapi juga menghadapi ketakutan terdalam manusia modern: keterputusan.
Film ini memposisikan dirinya di ruang perbatasan — antara agama dan okultisme, antara rasionalitas dan takhayul, antara generasi lama dan generasi baru.
Simbol paling mencolok adalah rosario (kalung doa) yang menjadi nama film sekaligus lambang perjalanan spiritual sang tokoh. Rosario muda — yang tak lagi berdoa dan tak percaya pada roh — justru terpaksa menempuh perjalanan mistik yang ironis.
Ritual-ritual yang ia temukan bukan sekadar dekorasi, tapi ekspresi dari kebutuhan manusia akan tatanan kosmik yang melampaui nalar.
Di tengah dunia yang menuntut efisiensi, film ini menunjukkan betapa yang sakral masih hidup dalam bentuk-bentuk yang tidak kita pahami. Bagi Rosario, kutukan bukanlah sekadar warisan darah, tapi juga warisan spiritual yang terlupakan.
Karakter dan Performansi
Emeraude Toubia memikul hampir seluruh beban film. Hampir setiap adegan adalah potret dirinya — terisolasi, ketakutan, dan perlahan kehilangan rasionalitasnya. Ia berhasil menampilkan pergeseran dari sosok profesional yang percaya diri menjadi perempuan yang rapuh dan penuh luka batin.
José Zúñiga sebagai sang ayah membawa dimensi emosional yang kuat. Dalam salah satu adegan tersisa, terungkap bahwa dialah sumber kutukan itu — membuat momen konfrontasi menjadi lebih dari sekadar pertarungan spiritual, melainkan pertarungan moral antara generasi.
Karakter nenek, meski jarang tampil secara langsung, menjadi figur simbolik penting. Ia bukan hantu, tapi penjaga tradisi — arwah dari dunia lama yang mencoba menyelamatkan keturunannya lewat bahasa yang hanya bisa dimengerti lewat ritual.
Dari sisi teknis, Rosario mengesankan lewat desain produksinya. Set apartemen yang tampak sempit menjadi laboratorium atmosfer: ruang antara dunia nyata dan spiritual. Efek praktikal (darah, tulang, gerak benda) digunakan dengan efisien, tidak berlebihan. Musik garapan Kevin Kiner memperkuat rasa “ritualistik” — dentum drum rendah, bisikan, hingga paduan suara gerejawi yang samar.Namun beberapa kritikus menilai film ini kehilangan momentum di paruh tengah: terlalu banyak repetisi tanpa pengungkapan baru. Plot kadang terasa berjalan di tempat sebelum menuju klimaks yang agak tergesa. Tetapi bila dibaca bukan sebagai thriller konvensional, Rosario justru bekerja di wilayah simbolik: ia lebih menyerupai trance sinematik ketimbang kisah linear.
Resonansi Tematik: Trauma, Warisan, dan Identitas
Di inti terdalamnya, Rosario berbicara tentang trauma antar-generasi — tema yang kini sering muncul dalam film-film horor kontemporer seperti Hereditary (2018) atau The Night House (2020). Kutukan dalam film tidak datang dari luar, tetapi dari dalam garis keturunan, dari hal-hal yang tidak pernah diselesaikan.
Rosario menjadi pewaris tidak hanya harta, tetapi juga dosa dan rahasia. Ketakutannya pada ritual dan roh hanyalah pantulan dari penolakan terhadap sejarah keluarganya sendiri.
Film ini juga menggambarkan ketegangan diaspora: bagaimana imigran Latin yang hidup di Amerika menghadapi disonansi antara spiritualitas leluhur dan sistem nilai modern. Dengan cara ini, Rosario bukan sekadar kisah individu, melainkan alegori bagi pengalaman kolektif banyak komunitas yang terombang-ambing antara dua dunia.
Ritual sebagai Jalan Pulang
Akhir film memperlihatkan Rosario melakukan ritual penebusan — bukan sebagai tindakan okultisme destruktif, tapi sebagai pengakuan akan keterhubungan dirinya dengan masa lalu. Momen ini menggeser makna film: dari horor menjadi spiritual. Ritual bukan sekadar untuk mengusir roh, tetapi untuk mengintegrasikan yang terpecah. Jika kita membacanya secara simbolik, ritual itu adalah metafora bagi kebutuhan manusia modern untuk berdamai dengan akar-akar yang ia tolak. Dengan mengakui warisan leluhur, Rosario akhirnya bisa menenangkan roh-roh di rumahnya — dan, barangkali, dalam dirinya sendiri.
Pada akhirnya, Rosario bukan film sempurna — beberapa bagian terasa repetitif, dan skripnya kadang lebih sibuk membangun suasana daripada kedalaman naratif. Namun ia tetap penting sebagai eksperimen spiritual dalam bentuk horor: menempatkan perdebatan antara modernitas dan tradisi dalam tubuh seorang perempuan muda yang terjebak di antara keduanya.
Felipe Vargas menunjukkan bahwa ketakutan terbesar manusia bukanlah pada setan, tapi pada bayangan warisan yang tidak mau kita akui.
Dalam dunia di mana sains menjawab segalanya, Rosario mengingatkan bahwa masih ada hal-hal yang tak bisa dihapus oleh pengetahuan: rasa bersalah, ingatan, dan doa yang tidak pernah selesai.
Bagi penonton yang mencari sensasi horor semata, film ini mungkin terasa lambat. Tapi bagi mereka yang peka terhadap simbol dan lapisan makna, Rosario bisa menjadi perjalanan batin yang mengganggu sekaligus menyembuhkan. Namun Rosario bukan sekadar tontonan tentang ketakutan atau kutukan keluarga. Di balik atmosfer gelap dan gema doa dalam kegelapan, film ini sesungguhnya membuka ruang tafsir yang lebih luas — ruang di mana psikologi, budaya, dan sosiologi saling bersinggungan.
Di titik inilah film Rosario menemukan maknanya yang paling menggugah: ia berbicara tentang manusia modern yang kehilangan bahasa untuk berbicara dengan hal-hal sakral. Ketika sains dan teknologi menjadi tumpuan utama, ritual dan simbol justru berubah menjadi sumber horor. Padahal, bisa jadi, horor itu muncul bukan karena roh jahat, melainkan karena kita sendiri yang tak lagi mampu menafsirkan maknanya.
Rosario adalah film dengan janji yang cukup besar: menggabungkan horor supranatural klasik dengan latar belakang budaya yang jarang dieksplorasi—imigran Latin, ritual Afro-Karibia, identitas yang terpecah. Suasana dan teknisnya kuat: desain produksi, efek praktikal, sinematografi—semuanya membantu menciptakan mood mencekam dan tak nyaman.
Namun sayangnya, janji tersebut tidak sepenuhnya tertunaikan: skripnya kadang berjalan setengah-setengah, karakter utama membuat pilihan yang tidak meyakinkan, dan beberapa twist terasa terburu-buru atau kurang dijelaskan. Rosario memang tidak buruk, namun juga bukan yang terbaik dalam genre. Rating film : ★★★☆☆ (Lukman Hqeem)